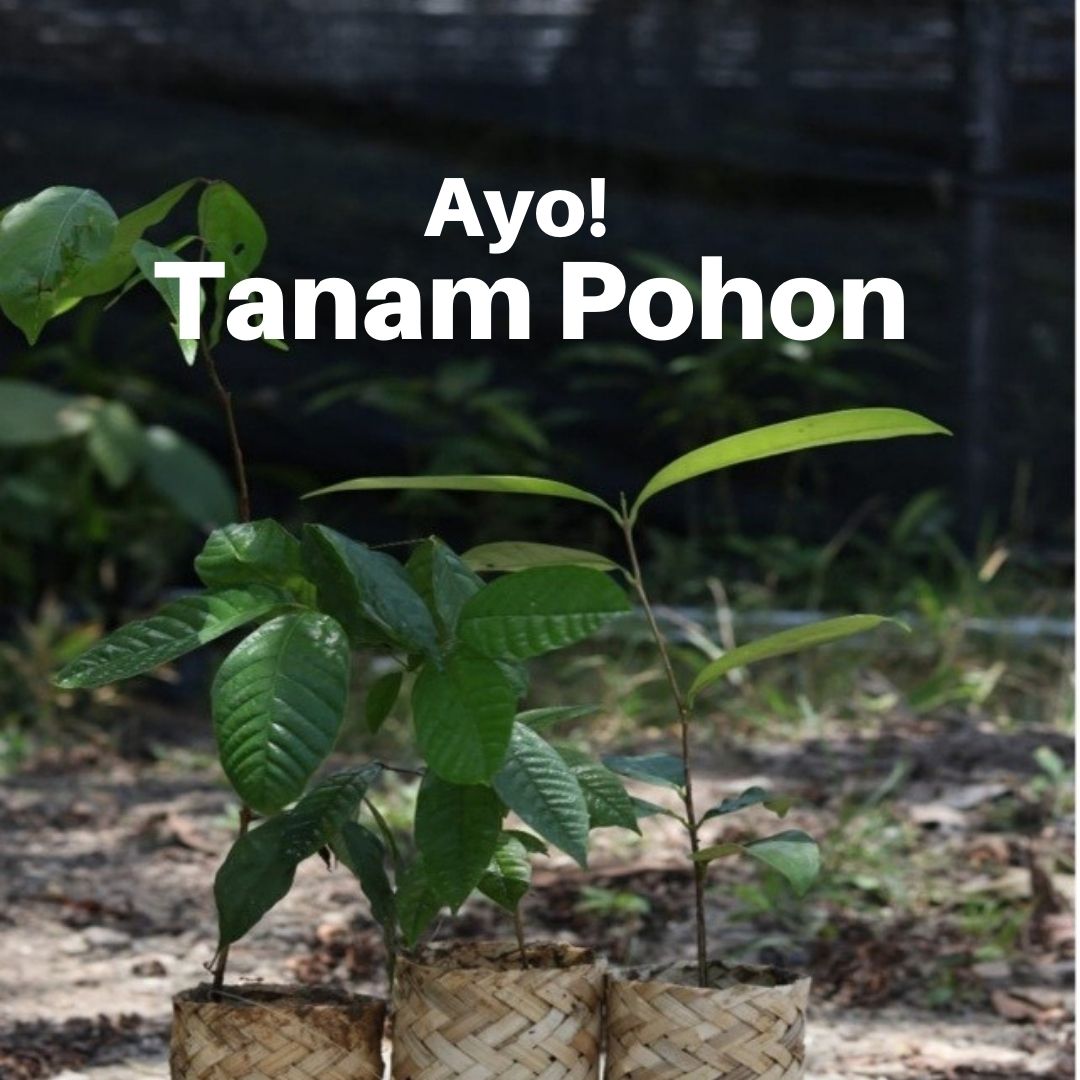Mahawan Karuniasa
Jakarta, 7 November 2025
COP30 di Belém akan digelar saat laporan-laporan sains global menunjukkan percepatan krisis iklim. Wilayah rentan terutama di negara berkembang dan tertinggal semakin merasakan dampaknya. Pertanyaannya hanya satu, apakah sistem politik, para pemimpin, siap mengikuti sains?
Menjadikan Amazon sebagai Poros Diplomasi Iklim Global
Brazil menegaskan tema besar COP30: Climate Action for People and Nature, sebuah pendekatan yang memadukan mitigasi, adaptasi, keadilan iklim, dan perlindungan hutan hujan tropis. Brasil dalam berbagai forum iklim sebelumnya, COP27, COP28, dan KTT Amazon 2023, berulang kali menegaskan bahwa dunia tidak lagi memiliki “kemewahan untuk menunda” aksi iklim dan bahwa Amazon harus menjadi poros utama solusi global.
Semangat inilah yang nampaknya mewarnai diplomasi Brasil menjelang COP30. Dalam Provision Agenda and Annotations COP30 memuat fokus pada penguatan Global Stocktake, pembaruan NDC pasca-2030, operasionalisasi Loss and Damage Fund, serta Just Transition Work Programme.
Brasil berupaya memanfaatkan kesempatan historis ini untuk menggeser orientasi perundingan: dari sekadar komitmen, menuju implementasi berbasis bukti ilmiah dan keadilan global. Dengan latar belakang catatan deforestasi historis, namun juga komitmen restorasi besar-besaran, COP30 secara politis dapat menjadi panggung bagi Brasil untuk untuk mengambil peran lebih dalam menghadapi iklim global, khususnya bersama negara-negara Selatan.
Merangkai Pesan Keras UNEP dan Sains Iklim Terbaru
Laporan United Nations Environment Programme (UNEP), yaitu Emissions Gap Report 2025 memberikan gambaran ilmiah paling terang tetapi paling gelap: dunia menuju pemanasan 2.5–2.9°C pada akhir abad, jauh melampaui batas aman 1.5°C.
Tanpa peningkatan ambisi mitigasi tiga kali lipat sebelum 2035, setiap tahun penundaan berarti peningkatan risiko bencana non-linear. Dokumen Adaptation Gap Report 2024 juga menunjukkan krisis serius: kebutuhan pendanaan adaptasi mencapai USD 300 miliar per tahun, namun dukungan internasional stagnan, bahkan menurun di beberapa negara.
Kedua laporan tersebut memperkuat pesan sains dalam proses COP: bahwa NDC generasi berikutnya harus berbasis sains, bukan sekadar hasil kompromi politik. Dan ketika gap mitigasi serta adaptasi justru melebar, COP30 menjadi titik terakhir untuk menyeimbangkan komitmen global dengan batas daya dukung bumi.
WMO: Dunia Mengalami Perubahan yang Tak Lagi Bersifat Linier
Peringatan paling kuat datang dari World Meteorological Organization (WMO). Laporan State of the Global Climate 2024 yang dirilis pada Maret 2025 memperlihatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terpanas dalam sejarah pencatatan suhu modern. Lautan mencatat pemanasan ekstrem, memicu bleaching massal terluas pada terumbu karang global, sementara intensitas gelombang panas meningkat drastis di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan.
Tambahan lagi, Global Annual to Decadal Climate Update 2025–2029 menegaskan probabilitas dunia menembus 1.5°C dalam satu tahun kalender kini mencapai lebih dari 80%, sebuah alarm ilmiah yang tidak bisa dituangkan lebih keras lagi. Dengan data multi-sumber dari satelit, stasiun cuaca, serta pengamatan laut, WMO menggarisbawahi bahwa dinamika iklim tidak lagi bergerak gradual melainkan akseleratif. Di sinilah COP30 menjadi forum moral: negara-negara harus menjawab apakah mereka menerima sains atau masih menundanya demi kenyamanan ekonomi dan politik sesaat.
Carbon Colonialism, Pembiayaan Hijau, dan Teknologi Kontroversial
Seperti COP sebelumnya, COP30 juga diwarnai isu-isu yang tidak masuk dalam dokumen resmi namun membentuk suasana negosiasi. Konsep carbon colonialism menjadi perdebatan besar, terutama terkait ekspansi pasar karbon global yang dinilai berpotensi mengeksploitasi hutan tropis dan masyarakat adat. Investasi energi fosil masih berada pada level USD 1 triliun per tahun, menunjukkan bahwa “perekonomian dunia belum siap melepaskan masa lalu”.
Di sisi lain, beberapa negara mulai mengangkat diskusi mengenai Solar Radiation Modification (SRM) sebagai opsi darurat, memicu kekhawatiran tentang moral hazard dan risiko lintas batas. Isu keadilan transisi energi menjadi semakin penting, terutama setelah banyak studi menunjukkan jutaan pekerjaan berisiko dalam proses transformasi industri. COP30 dimungkinkan menempatkan semua isu ini dalam konteks: transisi hijau tidak boleh menjadi transisi yang eksploitatif, dan tidak boleh meninggalkan kelompok rentan di belakang.
Membaca Krisis Risiko sebagai Krisis Ekosistem Kehidupan
Badan PBB lainnya, United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) melalui Global Assessment Report (GAR) 2025 Resilience Pays memberikan pesan strategis bagi COP30: bahwa investasi ketahanan (resilience) jauh lebih murah daripada biaya bencana. Laporan tersebut menyebutkan kerugian ekonomi global akibat bencana meningkat lima kali lipat dalam dua dekade terakhir.
Lebih dari 90% bencana terkait dengan cuaca ekstrem yang diperparah perubahan iklim. Sementara pendanaan DRR global belum mencapai 10% dari kebutuhan minimum. UNDRR menegaskan bahwa risiko kini bersifat sistemik: perubahan iklim memperbesar kerentanan sosial, infrastruktur, keuangan, bahkan politik. Permintaan untuk memperkuat Early Warning for All, adaptasi berbasis ekosistem, serta integrasi ketahanan dalam seluruh pembiayaan iklim menjadi rekomendasi kunci untuk Belém. COP30 harus menjadi arena untuk mensinergikan risk-informed climate action pendekatan yang saat ini masih terfragmentasi di banyak negara.
Politika Pembiayaan: Keadilan Global Masih “Menggantung” di Ruang Negosiasi
Salah satu potensi perdebatan paling keras di COP30 adalah pembentukan New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG). Negara berkembang meminta pendanaan minimal USD 600–800 miliar per tahun, sementara negara maju berusaha menetapkan angka lebih rendah dengan mekanisme alternatif seperti blended finance. Pengalaman kegagalan mencapai target USD 100 miliar selama lebih dari satu dekade membuat isu kepercayaan (trust deficit) menjadi fondasi diskusi.
Melalui berbagai kesempatan, Brasil, Indonesia, India, dan Afrika Selatan memiliki kesamaan dalam mengambil posisi tegas: tanpa pembiayaan memadai, tidak ada transisi energi yang adil, tidak ada adaptasi yang efektif, dan tidak ada strategi kehilangan-kerusakan (loss and damage) yang realistis. Di tengah ketegangan geopolitik global dari krisis pangan, ketidakstabilan finansial, hingga konflik, COP30 akan menjadi barometer apakah dunia masih bisa bekerja sama, atau masuk lebih dalam ke era fragmentasi iklim.
Indonesia: Posisi, Tantangan, dan Peluang di COP30
Indonesia memasuki COP30 dengan posisi yang semakin strategis. Sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga dunia, serta negara dengan salah satu garis pantai terpanjang, Indonesia berada dalam persimpangan: korban serius perubahan iklim sekaligus aktor kunci solusi iklim global. Tantangan Indonesia terletak pada pemenuhan target Enhanced NDC 2030 dan sekaligus menyiapkan transisi menuju Second NDC pasca-2030.
Laporan UNEP, WMO, dan UNDRR memperlihatkan urgensi untuk memperkuat implementasi FOLU Net Sink 2030, revitalisasi sistem energi, serta percepatan adaptasi berbasis komunitas dan ekosistem. Indonesia menghadapi kendala pendanaan, kapasitas teknologi, serta koordinasi lintas sektor, namun COP30 juga dapat membuka peluang strategis: diplomasi hutan tropis bersama Brasil dan Kongo, penguatan posisi di pasar karbon global berbasis integritas, serta peluang mendapatkan akses pendanaan transisi energi dan adaptasi skala besar. Momentum Belém perlu dimanfaatkan Indonesia untuk menegaskan paradigma baru: bahwa solusi iklim hanya mungkin bila pembangunan nasional berbasis keberlanjutan jangka panjang, bukan sekadar carbon accounting.
COP30 sebagai Titik Kesadaran Global
Menggabungkan pesan UNEP, WMO, dan UNDRR, COP30 harus dibaca sebagai peringatan terakhir sekaligus peluang terakhir. Brasil yang menekankan bahwa “Amazon adalah paru-paru terakhir planet ini” bukanlah metafora, melainkan realitas ekologis. Jika COP30 mampu melahirkan NDC generasi baru berbasis sains, skema pendanaan yang adil, dan roadmap transisi hijau yang implementatif, dunia masih memiliki peluang menghindari skenario bencana.
Jika gagal, Belém akan dikenang bukan sebagai tempat harapan, tetapi sebagai tempat dunia menyadari krisis, namun tetap tidak bertindak. Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, COP30 adalah ruang maupun panggung untuk memperjuangkan keadilan iklim global, sekaligus menentukan bagaimana mereka membentuk masa depan sebelum masa depan itu menentukan mereka.
***