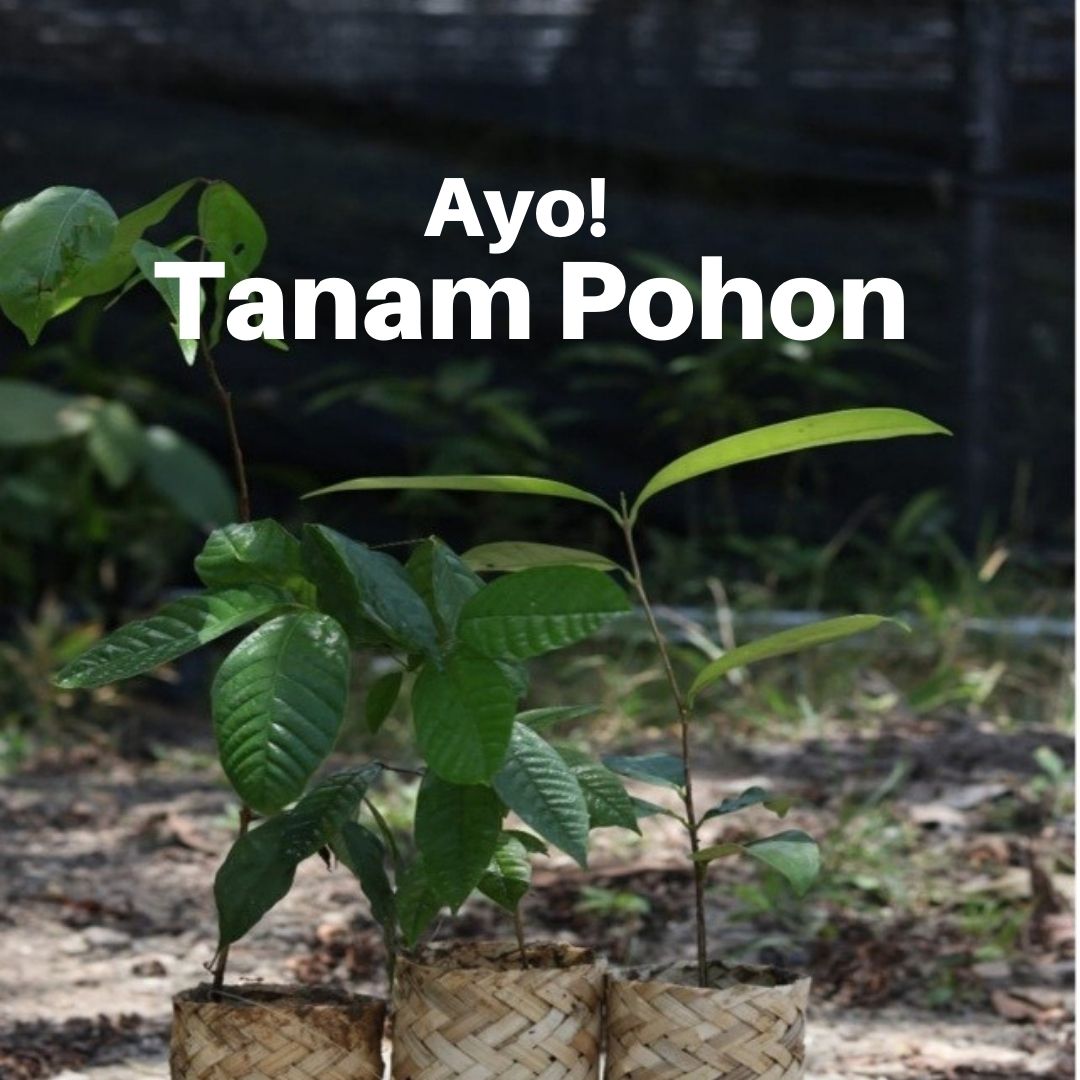Pengelolaan secara seimbang dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial menjadi kunci untuk pemanfatan sumber daya lahan gambut secara berkelanjutan.
Penting juga untuk memastikan gambut dikelola berdasarkan kajian ilmiah berdasarkan situasi di lapangan karena karakteristiknya yang berbeda-beda.
Demikian terungkap dalam the Internasional Seminar on Tropical Peatland “”Peatlands for Environment, Food, Fiber, Bio-energy and People” yang diselenggarakan Perkumpulan Masyarakat Gambut Indonesia (HGI), Kamis-Jumat, 21-22 Oktober 2021.
Seminar dibuka oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diwakili oleh Kepala Badan Litbang Pertanian Dr Fadjri Jufri dan dihadiri peneliti, praktisi, dan pengambil keputusan dari dalam dan luar negeri.
Dalam sambutannya yang dibacakan Dr Fadjri Jufri, Menteri Syahrul Yasin Limpo menyatakan lahan gambut bisa menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan pangan, serat, dan energi, dan berbagai kebutuhan masyarakat.
“Pemanfaatan gambut harus tetap memperhatikan aspek lingkungan agar tidak terjadi degradasi dan pemanfaatan bisa berkelanjutan,” katanya.
Pelaksana Tugas Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Reliantono menyatakan, untuk memastikan pengelolaan gambut berkelanjutan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2014 yang diperbarui dengan PP 57 tahun 2016 dan peraturan pelaksananya.
Berdasarkan PP Gambut, terdapat 12,3 juta hektare lahan gambut dengan fungsi budidaya dan 12,2 juta hektare dengan fungsi lindung.
“Pemanfaatan gambut untuk budidaya tetap harus menjaga keseimbangan tata air gambut sehingga mencegah dari kerusakan,” katanya.
PP Gambut juga mengamanatkan untuk dilaksanakannya restorasi. Sejauh ini, ungkap Sigit, sudah ada 294 unit usaha yang memanfaatkan lahan gambut yang sudah melakukan restorasi dengan total luas areal mencapai 3,6 juta hektare.
Director Sarawak Tropical Peat Research Institute Lulie Melling, Ph.D menyatakan potensi gambut harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
Dia mengingatkan pemanfaatan gambut harus berbasis situasi di lapangan karena karakteristik gambut yang khas yang berbeda-beda dari satu area dan area lainnya.
Lulie Melling juga menekankan konsep pengelolaan gambut yang berbasis penelitian gambut tempered yang memiliki empat musim, tidak bisa diterapkan di lahan gambut tropis seperti yang ada di Malaysia dan Indonesia.
“Dengan banyak karakteritistik gambut, maka praktik terbaik pengelolaan gambut berbeda-beda. Tidak bisa gambut dikelola hanya berdasarkan sejarah atau data lama, apalagi jika ada agenda tersembunyi,” katanya.
Terlantar
Ketua Umum HGI Profesor Supiandi Sabiham menyatakan berdasarkan data Kementerian Pertanian, masih ada sekitar 40% lahan gambut yang terlantar, tidak dikelola dan mengalami degradasi.
Jika lahan tersebut dibiarkan maka bisa memicu kerusakan yang lebih parah juga kebakaran lahan yang akhirnya memicu isu negatif dalam pengelolaan gambut.
Oleh karena itu, Supiandi mengajak koleganya sesama peneliti untuk terus melakukan penelitian pemanfaatan gambut secara berkelanjutan.
“Mendukung pengelolaan gambut yang seimbang dari sisi produksi dan konservasi menjadi tantangan bagi seluruh peneliti,” katanya.
Pakar ilmu tanah Universitas Kyoto, Jepang Profesor Shinya Funakawa mengungkapkan hasil penelitian yang membuktikan tanah gambut tidaklah ‘semiskin’ yang dibayangkan.
“Tanah gambut tidak selalu miskin unsur hara jika dibandingkan dengan tanah mineral,” kata dia.
Profesor Shinya memaparkan hasil penelitiannya dengan sampel dari sejumlah plot di 4 lokasi.
Lokasi tersebut adalah di Hutan Lindung Naman, Sarawak, Malaysia; kebun kelapa sawit dan lahan yang berdekatan dengan hutan sekunder di Kalimantan Barat; kebun kelapa sawit dan lahan yang berdekatan dengan hutan sekunder di Riau; dan hutan alam primer dengan berbagai material induk tanah di Kalimantan Timur.
Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sampel tanah pada kedalaman 30-50 cm selama lebih dari datu kalai dalam sebulan selama satu tahun. Sampel kemudian dianalisis setelah dilakukan filtrasi.
Hasilnya, tingkat keasaman (pH) gambut memang lebih rendah daripada tanah mineral. Namun kandungan unsur hara seperti Cl, SO4, K, Ca Mg, dan N menunjuk tidak lebih miskin dibanding tanah mineral.
Penelitian tersebut menunjukan potensi lahan gambut untuk kegiatan budidaya. Apalagi lahan gambut umumnya memiliki topografi mendatar dan kompak pada satu hamparan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Indroyono Soesilo, yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) mengungkapkan, tantangan yang dihadapi dalam pegelolaan gambut diantaranya adalah soal cadangan air dan karbon, subsidensi, dan pencegahan kebakaran.
Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Gambut No 71 tahun 2014 yang diperbarui dengan PP 57 tahun 2016 dan peraturan pelaksananya, muka air gambut dibatasi paling rendah 0,4 meter dari permukaan.
Terkait PP Gambut, menurut Indroyono, sebanyak 68 pemegang izin hutan tanaman yang telah membuat dokumen pemulihan dengan luas areal mencakup 2,2 juta hekatre dengan 5,669 unit titik pemantauan penaatan dan 8.012 sekat kanal yang dibangun.
“Tujuan dari pengelolaan gambut untuk hutan tanaman adalah mengatur tinggi muka air agar gambut tetap lembap, bisa mencegah kebakaran dan subsidensi, namun tetap bisa optimal untuk pertumbuhan tanaman,” katanya.
Indroyono menyatakan pemantauan dan pengendalian di lapangan terus dilakukan untuk memastikan tinggi muka air dan karakter gambut.
Menurut Indroyono, penerapan praktik terbaik pengelolaan gambut oleh manajemen hutan tanaman diharapkan bisa mendukung tersedianya bahan baku kayu yang dibutuhkan untuk memasok industri di tanah air.
APHI menargetkan ekspor produk hasiil hutan kayu dan non kayu bisa mencapai 60 miliar dolar AS di tahun 2045 dan menciptakan lapangan kerja langsung bagi 6,5 juta orang.
Spesies Alternatif
Sementara itu peneliti dari Sinar Mas Forestry Corporate R&D, Budi Tjahjono menjelaskan untuk mengimplementasikan praktik terbaik pengelolaan gambut, pihaknya melakukan penelitian untuk pengembangan spesies tanaman alternatif selain Acacia Cracicarpa.
“Penelitian dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UGM, dan Deltares,” katanya.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Siak dengan 14 lokasi percobaan. Spesies tanaman yang diteliti diantaranya adalah balangaran (Shorea balangaran), gelam (Meulaleuca leucadendra), geronggang (Cratoxylon arborescens), dan terentang (camnosperma coriaceum).
Spesies tanaman yang dicari adalah memiliki pertumbuhan yang cepat dan karakteritik serat yang sesuai dan lebih tahan basah, dengan muka air paling rendah antara 0-0,25 meter dari permukaan.
Menurut Budi, dengan tinggi muka air tersebut tanaman yang dimafaatkan saat ini, akasia cracicarpa memang masih bisa tumbuh cepat pada usia 0-6 bulan.
Namun kemudian kemudian melambat dengan tingkat kematian yang tinggi. Sementara spesies lain seperti balangeran, gelam, dan geronggang masih bisa tumbuh dengan baik.
Budi juga mengungkapkan, pihaknya bersama KLHK juga melakukan penelitian perbenihan dan pembibitan untuk spesies-spes alternatif tersebut.
Hasilnya, balangeran dan geronggang sudah bisa diperbanyak dengan memanfatkan teknologi tussie culture sehingga menjamin kualitan pohon yang dihasilkan.
Dari hasil penelitian, kata Budi, balangeran dan gelam potensial untuk dikembangkan sebagai tanaman di hutan tanaman karena memiliki produktivitas tinggi mencapai masing-masing 45,8 m3/ha per tahun dan 39,77 m3/ha per tahun.***